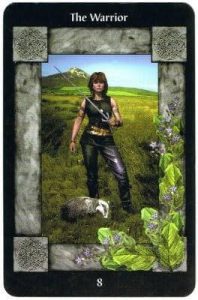Pada mulanya catatan ini aku simpan dalam memory otaku, pernah sesekali meninggalkanku,muncul kembali,hilang lagi.Timbul tenggelam seperti gelombang radio AM pada malam hari.
Dua puluh satu tahun kemudian catatan ini muncul kembali. Aku padukan intinya dengan impian dan khayalku.Isinya pun menjadi lain dari aslinya. Dan beginilah jadinya:
***
Tingkat perkembangan desa ini biasa-biasa saja.Dari tahun 90-an sampai tahun 2000-an kategorinya tetap Desa Swasembada.Pertumbuhan ekonominya selalu di bawah rata-rata nasional. Begitu juga angka kemiskinanya.Ini seperti desa yang tak siap berkembang.
Desa ini tidak memikat pendatang.Tidak menawarkan harapan hidup nan layak.Tidak pula menjanjikan masa depan yang indah, tapi sangat mengancam dan menakutkan.
Mereka yang datang tanpa bekal cukup, terpinggirkan.Yang tak kebagian kue pertumbuhan di sektor non formal, bertahan dengan cara menyimpan selaksa gerutu dan sedikit dendam.Kebanyakan penduduk aslinya tidak mempunyai kebanggaan atas desanya.
Satu-satunya daya pikat bagi orang luar desa untuk bertandang ke desa ini adalah tersiarnya kabar tentang seorang tabib yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit dengan satu macam ramuan.
Luas wilayah desa ini sekitar 174 hektare,terbagi atas tiga dusun.Masing-masing dusun dipimpin Kepala Dusun (Kamituo).Dari ketiga dusun itu, yang paling menonjol adalah dusun ini –berdasarkan luas wilayah,tingkat pendidikan dan populasi penduduknya.Saya sendiri lahir di desa ini tepatnya di dusun 3 dan menjadi kamituo di dusun 1.
Mungkin karena data monografi yang menonjol itulah, berbagai permasalahan sosial kerap muncul ke permukaan;saling sikut,jegal menjegal dan yang lainya. Kata orang luar,dusun 1 tidak begitu nyaman untuk ditinggali.
Saya pernah secara tidak sengaja berbincang-bincang dengan seorang pendatang dari luar kota di warung kopi tentang kondisi sosial masyarakat dusun ini.Pendatang itu tinggal bersama isterinya yang menjadi bidan desa di dusun ini.
Ia mengatakan bahwa dusun ini tidak begitu nyaman untuk ditinggali olehnya.Hal ini berdasarkan hitungan daya dukung wilayahnya, sumber air, tata dusun, jejaring transportasi, dan lain-lainnya.
Saya kira ia benar.
Kehidupan di dusun ini memang terasa tegang. Mudah sekali terjadi pro kontra diantara warga,dari persoalan sepele sampai yang beberapa pele .
Pernah juga saya bercengkerama dengan seorang teman membicarakan tentang hal itu.Sebut saja namanya Bang Al.Ia adalah salah satu perangkat desa di “desa ini” lebih tua dari usia saya.
Ia pamong yang bagiku paling liberal. Ke mana-mana pakai penutup kepala, banyak pengalamanya,banyak pula temanya termasuk berteman dengan bapak saya.Ia lahir,hidup,tumbuh,beranak-pinak dan meninggal di dusun ini.
Setahuku ia bisa tidur di mana saja yang ia mau, di tempat-tempat hiburan, yang ia datang malamnya, dan ia tertidur di situ sampai pagi. Saya sering menemaninya.Ia ke mana-mana bermotor. Ganti-ganti motornya.
Di awal-awal saya menjabat kamituo di “dusun ini” oleh Bang Al saya disarankan untuk serawung dengan masyarakat setempat. Saya senang-senang saja menerima saranya. Pertama, karena saya sama sekali buta tentang dusun ini. Jika pun saya tahu tentang kondisi sosiologis tentang dusun ini, itu hanya kabar burung dari orang-orang luar dusun yang absurd.
“Serawung karo cah nom-nom” katanya
“Ra ketang seminggu pisan.Sing penting ngetok ning kene”lanjutnya.
Pada hari pertama Bang Al mengajak saya keliling dusun ini, singgah di rumah-rumah yang dianggap tokoh masyarakat dan warung-warung kopi. Ia perkenalkan aku sebagai “kamituo dusun ini”.
“Kamituo dusun I” jawabnya,setiap kali orang bertanya kepadanya tentang diriku. Bang Al memperkenalkan saya pada tokoh-tokoh itu dan orang-orang yang nyangkruk di warung.
“Oh…!” kata mereka,mendengar jawaban Bang Al.
Hari itu, saya juga diajak singgah ke salah satu temanya yang bekerja sebagai pengepul barang bekas. Dari situ saya tahu ia juga pernah menjadi pengepul barang bekas.
Dengar-dengar ia pernah tinggal di Gresik, sebelum menjabat pamong di desanya.Ia terbuka soal kehidupan pribadinya. Kata orang, selentingan kabar yang saya dengar, Bang Al dulu semasa remajanya termasuk pemuda yang Bengal di dusunya:pemberani dan berwawasan luas.Tak terlalu jelas juga ingatanku tentang hal itu.
Di rumah temanya itu, Bang Al disapa “yan”.Seperti kebanyakan orang yang menyapanya setiap kali berbicara denganya.Dalam hati saya merasa heran dengan sapaan itu.Baru dikemudian hari saya tahu kalua dia menjabat Kebayan di dusun 2.
Pada saat saya sedang santai bersamanya sambal menikmati udud di warung kopi luar desa,Bang Al memberi saya sebuah pertanyaan.Entah dari mana asal muasalnya pokok bahasanya tiba-tiba ia bertanya.
“Kue iku urip opo ora?” tanyanya.
“Yo,urip le”jawabku
“Nak urip,opo cirine urip –ora ciri-cirine wong urip—terus ning endi dununge uripem?” lanjutnya.
(bersambung)