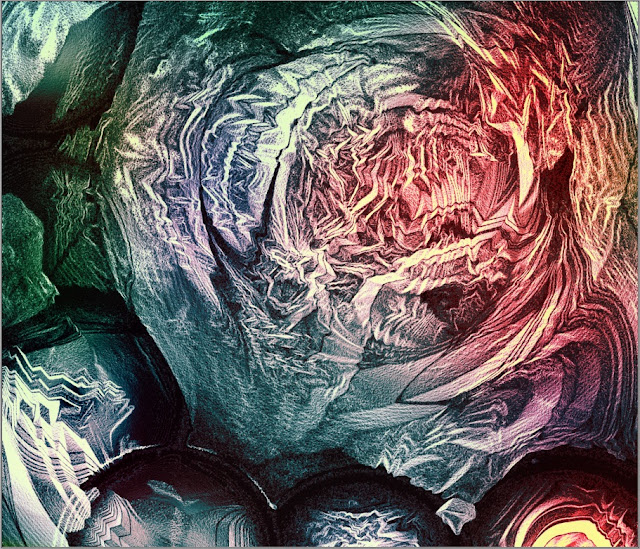
Ditulis oleh : I Ketut Sawitra Mustika
Dulu sekali, jauh di masa silam, metafisika punya reputasi mentereng dan terhormat. Namun seiring waktu berlalu, ia dianggap tidak saintifik dan mubazir. Manusia, demikian para orang pandai menasehati, mesti menyerah berusaha mengetahui hakikat fundamental dari realitas, karena hal tersebut mustahil. Saran ini tidak pernah benar-benar diamalkan. Metafisika terlalu sulit disingkirkan sebab ia adalah bagian tak terpisahkan dari kodrat homo sapiens.
Ketika masih berjaya, metafisika dielu-elukan sebagai ratu yang melahirkan ilmu pengetahuan. Pernyataan yang masuk akal, sebab sains dan filsafat, yang pada mulanya tidak dibedakan, lahir dari usaha yang berpangkal pada akal spekulatif. Ketika Thales mengatakan materi primitif penyusun benda-benda di dunia adalah air, ia tidak lagi mengikursertakan mitologi, otoritas keagamaan, atau entitas ilaiah untuk menafsirkan dunia. Demikian pula kasusnya ketika Anaximander mengajarkan bahwa arkhe, prinsip pertama penyebab dari segala benda-benda, adalah to apeiron, infinite, atau ketakterbatasan. Sebab, bila terbatas, maka materi kosmik akan kehabisan energi dalam mencipta.
Mereka tak pula bereksperimen, sebab ikhtiar mengetahui elemen paling fundamental dan mendasar senantiasa melampaui tampakan dan jangkauan indra. Mereka sepenuhnya menggunakan akal spekulatif. Dan metafisika secara inheren bersifat spekulatif. Kebenaran dan ketidakbenaran proposisinya tidak dapat dibuktikan secara empiris, baik melalui observasi maupun eksperimen.
Saking prestisiusnya, Aristoteles menamai metafisika sebagai filsafat pertama. Para filsuf Yunani Kuno tak mengenal istilah metafisika. Term ini baru lahir pada Abad Pertama SM, ketika Adronicus dari Rhodes, seorang editor, mencari judul yang tepat bagi 14 risalah Aristoteles yang tidak dapat diklasifikasikan dalam logika, etika, dan fisika. Tampaknya ia memilih istilah metafisika untuk keperluan bibliografi, karena tulisan-tulisan di dalamnya diletakan setelah Physics (meta ta physika/setelah fisika). Namun penjudulan ini mungkin juga terkait dengan isinya (Grondin 2012,XXII-XXIII).
First philosophy, menurut Aristoteles, adalah sains yang bertugas mencari dan mendapatkan pemahaman teoretis mengenai Being qua Being (Being sebagai Being). Ia adalah sains dalam artian paling penuh karena mendiskusikan apa yang paling primer, dan membahas sesuatu yang darinya benda-benda partikular mendasarkan dirinya. First philosophy berbeda dengan sains-sains khusus, karena “tak ada dari mereka yang menginvestigasi Being qua Being dalam artiannya yang universal. Sebaliknya, masing-masing memotong bagian dari Being dan memperoleh pemahaman teoretis mengenai apa yang intrinsik pada dirinya seperti, sebagai contoh, yang dilakukan matematika” (Aristoteles 2016, 48/ 1003 a 20-25).
Perihal maksud sesungguhnya dari Being qua Being tidak dapat dibahas di sini, sebab uraiannya membutuhkan ruang sendiri. Yang jelas, filsuf pertama yang menelurkan konsep Being adalah Parmenides. Menurutnya, semua pemikiran mengacu pada sesuatu yang dipikirkan, dan karenanya memiliki Being sebagai isi. Pikiran mustahil mengacu pada Nothing karena tidak akan memiliki isi untuk dipikirkan. Dengan demikian, Not-Being tidak dapat dipikirkan.
Bila semua pemikiran mengacu pada sesuatu yang ada, maka Being di manapun sama. Being adalah produk terakhir dari abstraksi jika dibandingkan dengan isi pikiran partikular. Dari premis ini diturunkan ajaran Eleatik paling fundamental, yakni hanya Being tunggal yang ada atau Being itu adalah Ada. Menurut Parmenides, Being tak terciptakan, dan tak terhancurkan. Ia tidak dan tidak akan pernah tidak eksis. Selalu ada, kekal. Being juga tidak berubah, tunggal, secara kualitas homogen dan manunggal, dan tidak terbagi (indivisible). Namun ia juga adalah aktualitas jasmaniah yang menduduki ruang secara penuh, tanpa menyisakan ruang hampa sedikitpun (Windelband 1899, 59-61). Hanya Being yang nyata. Segala perubahan, pluralitas, gerakan, permulaan, dan kehancuran di dunia persepsi adalah ilusi.
Sejak Parmenides mengutarakan pemikirannya itu dalam syair berjudul On Nature, para metaphysician di dunia Barat sibuk mencari tahu apakah sesungguhnya Being itu; apakah arti dan makna sejatinya. Sekarang penyelidikan ini disebut sebagai ontologi, yakni diskursus rasional yang diperuntukkan khusus bagi Being dan artiannya pada level paling fundamental, yakni abadi dan tak terhancurkan.
Namun, di balik setiap kejayaan tersimpan kehancuran. Kejatuhan metafisika terjadi seiring dengan prestasi sains yang gilang-gemilang. Proposisi-proposisi sains tidak hanya dapat diuji secara intelektual, tapi juga secara empiris melalui observasi dan eksperimen. Perbedaan ini membuat sains, yang mulai memerdekakan diri dari filsafat sejak Abad ke-18, berhasil merengkuh capaian luar biasa dalam waktu singkat. Pengetahuan yang diproduksi sains juga sangat berguna bagi manusia.
Sementara di sisi lain, metafisika, dengan sejarah yang membentang selama 2000 tahun lebih, tak menghasilkan progres apapun. Tidak ada hasil selain cekcok dan polemik tidak berkesudahan. Metafisika dinilai tidak pantas lagi menyandang tugas menafsir dunia dan harus mundur dari gelanggang secara terhormat. Serahkan saja semua pada sains yang penuh pencapaian. Bahkan banyak yang menganggap pemikiran spekulatif harus enyah sepenuhnya, karena ia adalah cara bernalar yang sesat. Metafisika dinilai tidak memiliki urusan dan manfaat dengan kehidupan nyata, kabur, terlampau muskil, dan hanya terobsesi menghasilkan pengetahuan yang transenden. Singkatnya, tidak berguna dan tidak sadar diri sebab pengetahuan yang dicari melampaui kapasitas manusia dalam mengetahui sesuatu.
Kant, melalui Critique of Pure Reason, melancarkan serangan penghabisan yang mengakhiri riwayat metafisika tradisional. Kritik terhadap metafisika sudah lazim mengikutsertakan ajarannya. Ia dianggap sebagai penggali kubur metafisika yang sudah uzur. Filsuf asal Jerman ini menilai akal murni tidak akan dapat mengetahui hakikat sejati benda-benda, atau thing-in-itself, sebab pengetahuan dihasilkan melalui penggunaan intuisi (ruang dan waktu) dan kategori-kategori pemahaman yang sepenuhnya subjektif. Intuisi dan kategori adalah prasyarat benda-benda menampakkan dirinya pada kita, dengan kata lain syarat pengalaman, Karenanya benda-benda hanya akan hadir sebatas tampakan semata. Hakikat atau substratum-nya tetap di luar jangkauan pengalaman yang mungkin (Kant 1998, 115/Bxxv-I, 255/B149, 262/B161). Thing-in-itself hanya dapat diketahui bila manusia memiliki intuisi intelektual. Semenjak kita hanya memiliki intuisi sensible atau empiris, maka kemungkinan untuk mengetahuinya secara otomatis tertutup dengan sendirinya.
Segala bentuk pemikiran spekulatif yang mengklaim dapat menjangkau hakikat realitas sejati yang melampui penampakan, dengan demikian, hanya konsep kosong tanpa muatan objektif sama sekali. Manusia tidak akan pernah tahu apakah ada entitas objektif yang berkorespondensi dengan konsep-konsep tersebut atau tidak, karena kita tak memiliki data-data terkait. Perluasan menuju yang transenden tidak akan membawa kita ke mana-mana sebab intuisi, sebagai pemasok data-data, hanya terbatas pada objek-objek pengalaman. Dengan demikian apa yang dihasilkan metafisika tidak memiliki legitimasi. Pengetahuan yang absah hanya terbatas pada pengalaman yang mungkin.
Serangan terhadap metafisika dilanjutkan, salah satunya, oleh positivisme logis. Diktum utama aliran filsafat yang berpusat di Wina ini adalah semua pernyataan yang bukan tautologi baru bermakna jika, dan hanya jika, bisa diverifikasi, setidaknya secara prinsipiel. Ayer berpendapat bahwa tidak ada pernyataan yang mengacu pada realitas yang melampaui batasan pengalaman indrawi bisa memiliki makna apapun, karena secara prinsipiel tidak dapat diverifikasi.
Keberadaan monad-monad Leibniz yang tidak lain merupakan substansi sederhana penyusun benda-benda, misalnya, secara prinsipiel mustahil diverifikasi karena mereka immaterial sebab tidak memiliki bagian-bagian dan tidak tersusun dari komponen-komponen fisik (Leibniz 1991, 45). “Karenanya bisa dikatakan kerja-kerja dari mereka yang berusaha menggambarkan realitas demikian (melampui pengalaman indrawi yang mungkin) didedikasikan untuk memproduksi omong kosong” (Ayer 1952,34).
Kodrat Manusia sebagai Makhluk Berakal
Meskipun gempuran datang silih berganti, metafisika menolak mati. Ia terlalu liat untuk mundur dari gelanggang. Filsuf-filsuf besar tetap berspekulasi. Kant, jika dicermati, sejatinya adalah seorang metafisik, karena ia berusaha mencari tahu bagaimana metafisika bisa menjadi ilmu yang mungkin. Karya-karyanya mengilhami kelahiran pemikir-pemikir besar dalam sosok seperti Schopenhauer, Fichte, Schelling, dan Hegel. Dua nama terakhir dianggap sebagai salah dua pemikir spekulatif paling berbakat dalam sejarah pemikiran Barat. Heidegger juga sibuk memaknai kembali Being dan menjawab pertanyaan abadi metafisika: Mengapa ada sesuatu daripada tidak sama sekali? Pun dalam beberapa dekade terakhir iklim filsafat di negara-negara Anglo-Saxon dihangatkan kembali oleh kebangkitan minat terhadap pertanyaan-pertanyaan metafisik.
Lalu pertanyaannya, kenapa manusia tetap bermetafisika meski aktivitas ini tidak menghasilkan apapun? Jawabannya terletak pada hakikat akal itu sendiri. Menurut Kant, yang khas dari akal adalah ia selalu menuntut penjelasan lengkap dari suatu fakta. Untuk suatu fakta yang diketahui, akal selalu bertanya mengapa, dan mengapa, tanpa akhir. Tidak pernah ia puas dengan pemahaman yang dimiliki sebelum penjelasan lengkap, absolut, atau “the unconditioned“, yang tidak lagi memerlukan penjelasan lebih jauh, dapat tergapai (Rohlf 2010,195-6). Karenanya akal secara inheren metafisik dan manusia dipaksa merenungkan pertanyaan-pertanyaan metafisika, suka atau tidak suka.
“Akal manusia memiliki takdir aneh karena kognisinya yang dibebani dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat diabaikan, semenjak mereka diberikan sebagai problem-problem oleh hakikat akal itu sendiri, tapi (di saat bersamaan) juga tidak dapat dijawab, semenjak mereka melampaui setiap kapasitas dari akal manusia” (Kant 1998, 99/Aviii).
Metafisika sama sekali bukan aktivitas khas filsuf-filsuf ber-privilege dengan waktu luang melimpah. Awam pun punya kebutuhan yang sama. Bahan bakarnya adalah kefanaan, dunia yang penuh misteri, dan penderitaan. Singkatnya keheranan terhadap eksistensi dan dunia itu sendiri. Keheranan ini bermuara pada rasa ingin tahu. Hanya saja, berbeda dengan filsuf yang mengandalkan refleksi konseptual untuk menjawab keingintahuannya, hasrat mengetahui orang pada umumnya dipuaskan dengan hadirnya agama.
Agama, menurut Schopenhauer, adalah metafisika populer yang diperuntukkan bagi orang banyak. Refleksi bukan dianggap utama, tapi iman. Wahyu adalah sumber kebenarannya (Schopenhauer 1966,164). Eksistensi Tuhan, malaikat-malaikat, surga dan neraka, kehidupan setelah kematian, keselamatan di akhirat, dan reinkarnasi adalah spekulasi-spekulasi karena melampaui pengalaman yang mungkin, meskipun, tentu saja, mereka yang mengimani menganggapnya sebagai kebenaran absolut dan self-evident.
Agama menyediakan jawaban tentang asal-usul, alasan kenapa dunia eksis, dan siapa penciptanya. Di tengah kehidupan yang penuh lautan rasa sakit, derita, dan kecewa, agama menjamin bahwa eksistensi tidak-; tidak berakhir hanya pada kematian yang sunyi. Di akhirat nanti pembebasan dan kebahagian abadi telah menunggu selama dogma dijalankan sungguh-sungguh. Keyakinan-keyakinan ini adalah bukti nyata betapa metafisika begitu melekat erat dengan kehidupan, sebab dorongan untuk mengetahui realitas sejati senantiasa hadir dalam benak manusia. Spekulasi-spekulasi mengenai hakikat mendasar realitas tidak dapat kita buktikan kebenarannya, tapi di saat bersamaan kita tidak dapat melepaskan diri dari jeratannya seperti buruan terkena perangkap.
Jadi rasanya tidak keliru bila Heidegger menyatakan bahwa metafisika “termasuk kodrat manusia. Ia bukan divisi filsafat akademik maupun bidang dari gagasan arbitrer. Metafisika adalah peristiwa mendasar dari Dasein (eksistensi). Ia adalah Dasein itu sendiri” (Heidegger 1993, 109).
- Aristoteles, Aristoteles. 2016. Metafisika diterjemahkan oleh C. D. C Reeve. Indianapolis: Perusahaan Penerbitan Hackett Inc.
- Grondin, Jean. 2012. Pengantar Metafisika diterjemahkan oleh Lukas Soderstrom. New York: Universitas Columbia Press.
- Heidegger, Martin. 1993 “Apa Itu Methaphysics?” dalam Basic Writing diterjemahkan oleh HarperCollins Publisher Inc.
- Kant, Immanuel. 1998. Kritik Nalar Murni diterjemahkan oleh Paul Guyer dan Allen W. Wood. Cambridge: Pers Universitas Cambridge.
- Leibniz, G. W. 1991. Monadologi diterjemahkan oleh Nicholas Recher. Pittsburgh: Universitas Pittsburgh Press.
- Ayer, Alfred Jules. 1952. Bahasa, Kebenaran dan Logika. New York: Publikasi Dover, Inc.
- Rohlf, Michael. 2010. “Gagasan Nalar Murni” dalam (Paul Guyer ed.) Pendamping Cambridge untuk Kritik Kant terhadap Alasan Murni. Cambridge: Pers Universitas Cambridge.
- Schopenhauer, Arthur. 1966. The World As Will and Representation volume II diterjemahkan oleh E. F. J. Payne. New York: Publikasi Dover, Inc.
- Wildelband, Wilhelm. 1899. Sejarah Filsafat Kuno diterjemahkan oleh Herbert Ernest Cushman. New York: Charles Scribners Putra.
Latest Posts
- Patut Diduga SPBU 44 59202 Kaliori Rembang Kongkalikong dengan Mafia Solar Subsidi
- Pemerintah Kabupaten Rembang Fokus Tekan Angka Kemiskinan pada 2025
- Korban Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Rembang Tahun 2024 Meningkat Jadi 118 Orang
- Sejumlah Kepala Desa Temui Wakil Bupati Rembang Bahas Kasus Hukum Kepala Desa Pangkalan
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinarpus) Kabupaten Rembang Gelar Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan untuk Tingkatkan Daya Tarik Masyarakat dan Siswa
Categories
- Advetorial
- Bahasa Jawa
- Berita
- Cerita
- Daerah
- Entertainment
- Hukum
- Humaniora
- Infografis
- Kesehatan
- Kriminal
- Kuliner
- Lain-Lain
- Nasional
- Njajah Desa Milangkori
- Olahraga
- Olahraga
- Opini
- Otomotif
- Parenting
- Pariwisata
- Pendidikan
- Perekonomian
- Peristiwa
- Politik
- Ragam
- Ramadan
- Rembang Gemilang
- Sosial Budaya
- Uncategorized
- Warta Desa
- Wisata
















